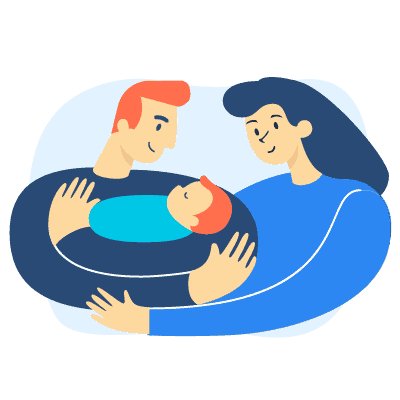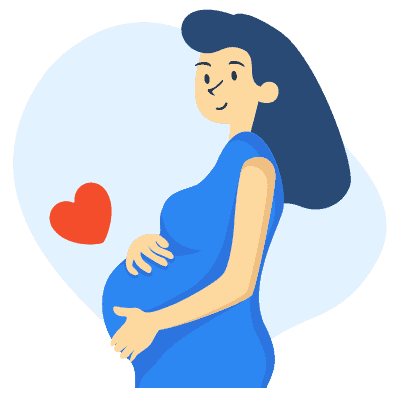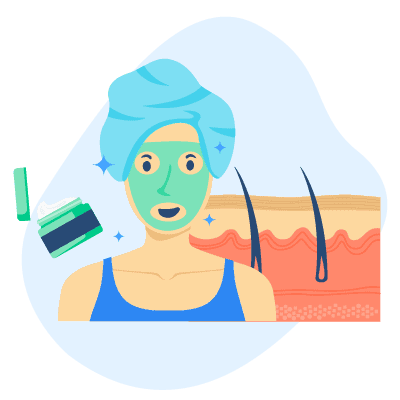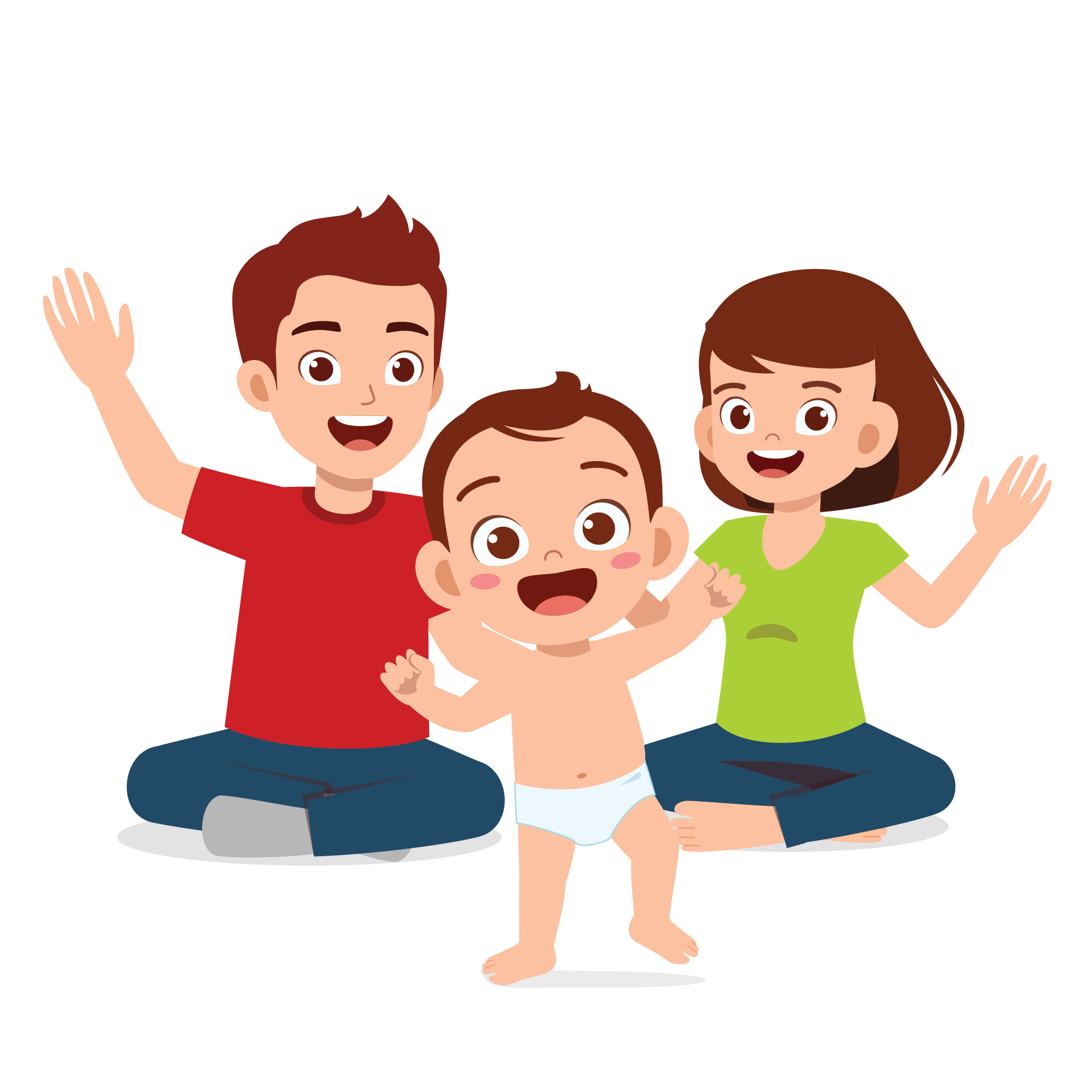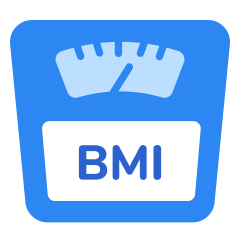Anda bisa menemukan kerumunan di konser musik atau pertandingan olahraga. Meski tampak biasa, keramaian yang padat dan tidak terkendali bisa membawa bencana. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahaya dan cara menyelamatkan diri dari kerumunan.

Apa itu kerumunan?
Kerumunan adalah kumpulan orang yang berada di satu lokasi dalam jumlah besar. Situasi ini sering terjadi dalam konser musik, pertandingan olahraga, atau acara keagamaan.
Selain itu, kerumunan atau crowd juga bisa muncul secara spontan, misalnya saat terjadi keadaan darurat atau terdapat diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan.
Hal ini berpotensi berubah menjadi situasi berbahaya bila kepadatannya sudah terlalu berlebihan dan timbul kepanikan di dalamnya.
Dalam situasi tersebut, kerumunan yang kacau dapat terjadi. Kondisi ini berisiko menimbulkan dampak yang fatal bagi manusia.
Contoh kerumunan dan bahayanya

Kerumunan dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti antrean panjang di pusat perbelanjaan selama diskon besar atau festival musik yang dipadati oleh ribuan orang.
Situasi ini bisa dikendalikan asal ada pengaturan yang jelas. Jika hal ini tidak ada, situasi dapat berubah menjadi kacau dan bahkan menimbulkan korban jiwa.
Contoh kerumunan kacau terjadi dalam tragedi Itaewon, Korea Selatan, ketika ribuan orang memadati gang sempit saat perayaan Halloween dan menyebabkan lebih dari 150 korban jiwa.
Contoh lainnya adalah tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, ketika kericuhan dan lemparan gas air mata memicu kepanikan massal yang menelan hingga 135 korban jiwa.
Terdapat dua bahaya yang bisa dipicu oleh kerumunan kacau, yaitu crowd crush dan stampede.
Crowd crush adalah suatu kondisi saat kepadatan ekstrem membuat seseorang terjepit sampai sulit bernapas dan bahkan hilang kesadaran.
Sementara itu, stampede adalah situasi ketika kepanikan massal menimbulkan gerakan tidak terkendali dari kerumunan yang meningkatkan risiko jatuh, terinjak, atau cedera lainnya.
Seberapa bahaya kerumunan yang kacau?
Cara menyelamatkan diri dari kerumunan
Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan diri di tengah kerumunan yang kacau.
1. Tetap tenang dan jangan panik
Panik hanya mengurangi kemampuan berpikir jernih serta membuat situasi semakin berbahaya.
Ambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Perhatikan situasi di sekitar agar agar Anda tetap waspada terhadap perubahan perilaku massa di dalam keramaian.
2. Perhatikan arah kerumunan
Orang-orang yang terjebak di dalam keramaian umumnya memiliki pola gerakan tertentu. Hindari melawan arus untuk mengurangi risiko jatuh atau terinjak.
Sebaliknya, ikuti arah gerakan massa sambil mencari peluang untuk bergerak ke tempat yang aman.